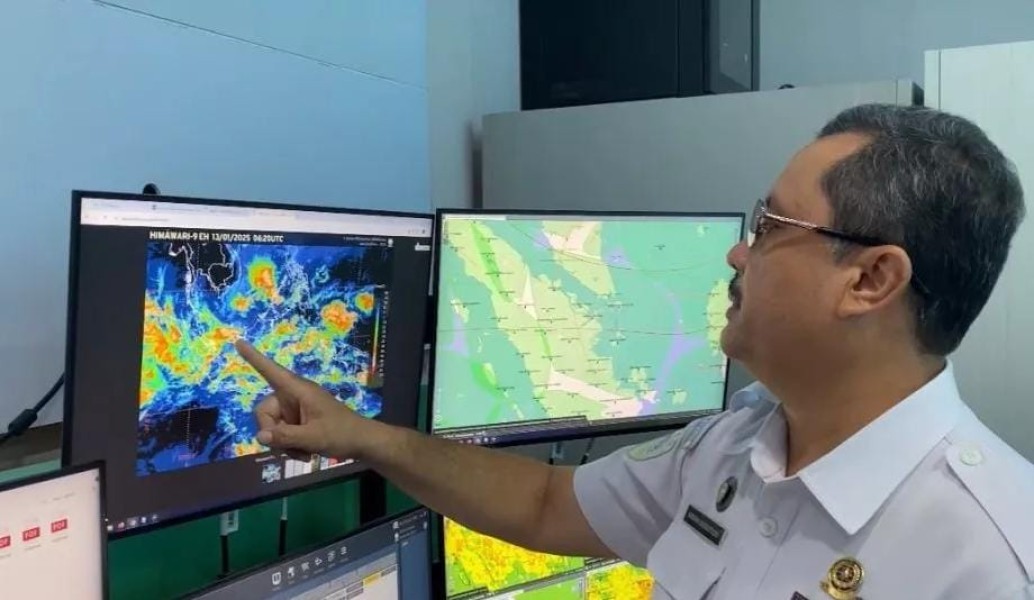Oleh: Irvan Nasir
KITA mungkin pernah hadir di sebuah acara resmi. Pidatonya panjang, tepuk tangannya lebih panjang. Seusai acara, seseorang berbisik, “Tadi beliau bicara apa?” Temannya menjawab jujur, “Kurang tahu. Tapi tepuk tangannya serempak.”
Sejak itu saya belajar satu hal: tepuk tangan tidak selalu sejalan dengan pemahaman.
- Baca Juga Balik Badan
Pidato Presiden Prabowo belakangan ini menarik disimak. Bukan karena gagasannya benar-benar baru, melainkan karena polanya terasa sangat familiar. Bangsa besar. Negara kuat. Ancaman dari luar. Seruan pengorbanan. Nada heroik yang berulang, seperti lagu lama yang diputar ulang, kadang dengan volume lebih tinggi agar semua ikut bertepuk tangan. Yang paling heroik, tentu saja: “Hidup Jokowi!”
Secara politis, ini mudah dibaca. Prabowo sedang merawat kesinambungan kekuasaan. Ia menegaskan loyalitas, menenangkan koalisi, dan mengirim sinyal stabilitas kepada elite politik. Dalam konteks transisi kekuasaan yang penuh kompromi, pidato semacam ini berfungsi sebagai lem perekat. Tidak salah. Bahkan mungkin perlu.
Masalahnya, fungsi pidato kenegaraan tidak berhenti pada kebutuhan elite.
Prabowo adalah produk paling matang dari dunia kampanye Indonesia. Hampir dua dekade hidup di panggung politik elektoral. Empat kali maju sebagai calon presiden. Ribuan mimbar dan tatapan jutaan pandang mata.
Dalam dunia seperti itu, ukuran keberhasilan paling cepat adalah tepuk tangan. Panjang berarti berhasil; pendek berarti ada yang kurang; entah diksi, intonasi, atau penutupnya tidak cukup heroik.
Dan urusan tepuk tangan, Prabowo memang ahlinya.
Namun panggung kini telah berubah. Ini bukan lagi lapangan kampanye, melainkan istana. Kursinya empuk, pendinginnya dingin. Pendengarnya bukan lagi massa yang digerakkan emosi, melainkan rakyat yang ingin kepastian. Di titik ini, pidato bukan lagi alat mobilisasi, melainkan instrumen akuntabilitas.
Sebagai kandidat, pidato memang tak perlu rinci. Angka dan tabel bisa menyusul. Yang penting keyakinan tumbuh. Itu hukum alam kampanye.
Sebagai presiden, hukumnya justru terbalik. Rakyat menunggu detail, bukan gema.
Detail itu pun sebenarnya sangat konkret: lapangan kerja, harga beras, sekolah anak, rumah sakit, dan satu pertanyaan dasar, apakah hidup besok terasa lebih ringan atau justru makin berat. Ini bukan soal ideologi besar atau pertarungan global. Ini soal dapur dan dompet.
Di sinilah jargon mulai terasa problematis. Nasionalisme memang penting, tetapi nasionalisme tidak otomatis menurunkan harga cabai. Retorika kedaulatan memang membakar semangat, tetapi tidak serta-merta memperbaiki layanan publik. Seruan pengorbanan terdengar mulia, tetapi publik berhak bertanya: pengorbanan siapa, untuk apa, dan sampai kapan?
Tanpa penjelasan itu, pidato mudah berubah menjadi kembang api politik: indah, terang, mengundang decak kagum, lalu habis tanpa sisa. Yang tertinggal hanya gema, bukan arah.
Sebagian pidato juga terasa lebih ditujukan ke audiens politik tingkat lanjut: elite partai, mitra koalisi, dan lingkar kekuasaan. Bagi rakyat kebanyakan, bagian ini sering lewat begitu saja. Padahal justru di situlah publik berharap kejelasan: keputusan apa yang akan diambil, prioritas apa yang dipilih, dan risiko apa yang berani ditanggung pemerintah.
Semakin tinggi jabatan, semakin mahal harga kata-kata. Setiap kalimat presiden membangun ekspektasi. Dan ekspektasi yang terlalu tinggi, tanpa peta jalan yang jelas, mudah berubah menjadi kekecewaan. Sejarah politik kita penuh dengan contoh: pidato yang membius di awal, lalu pelan-pelan kehilangan makna ketika realitas tak kunjung menyusul.
Dulu, ukuran pidato yang berhasil adalah riuh tepuk tangan. Kini ukurannya justru lebih sunyi: apakah rakyat pulang dengan perasaan paham. Tidak harus terharu. Tidak perlu berdiri. Cukup mengerti apa yang akan dikerjakan negara atas nama mereka.
Indonesia tidak kekurangan semangat. Kita juga tidak kekurangan pidato. Yang sering masih langka adalah kejelasan yang disampaikan dengan tenang, tanpa harus selalu heroik. Dalam situasi ekonomi yang menekan dan ketimpangan yang nyata, rakyat tidak sedang mencari orator ulung. Mereka mencari penunjuk arah.
Ketika presiden bicara, publik berharap mendengar arah yang tegas, pilihan yang jujur, dan batasan yang jelas. Tidak berputar-putar. Tidak sekadar menghangatkan ruangan. Bahkan dengan nada datar sekalipun, asalkan jalannya lurus.
Dan sering kali, dalam politik, kalimat paling penting justru bukan yang paling mengundang tepuk tangan, melainkan yang paling berani menjelaskan kenyataan.
Mungkin beliau lupa musim kampanye sudah lama berlalu. (*)









.jpg)